Opini
Snapback, Arogansi Telanjang E3 Terhadap Iran
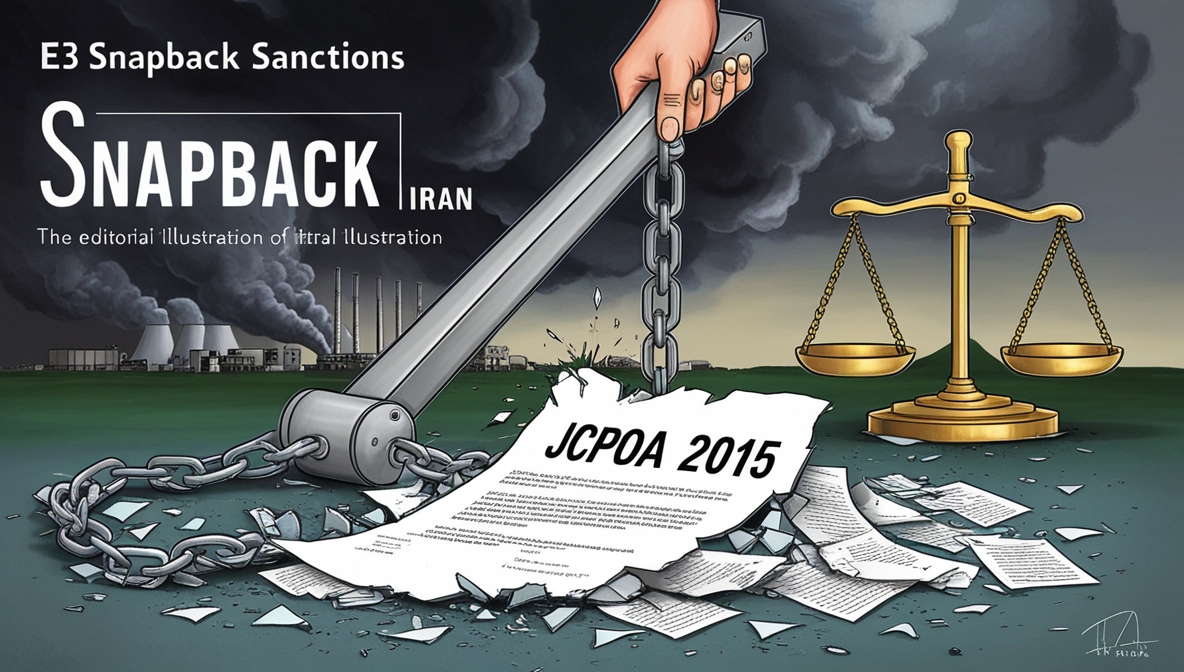
Ada sesuatu yang ganjil, bahkan mengundang tawa getir, ketika tiga negara besar Eropa—Prancis, Jerman, dan Inggris—dengan wajah penuh percaya diri mengumumkan pemicu snapback (sanksi) terhadap Iran. Kita bicara tentang sebuah mekanisme yang lahir dari JCPOA 2015, perjanjian nuklir yang pada kenyataannya sudah hancur sejak lama. Dunia menyaksikan bagaimana Amerika Serikat pada 2018 dengan angkuh keluar dari kesepakatan, Eropa hanya bisa diam seribu bahasa, dan Iran dibiarkan menanggung akibat. Namun kini, E3 datang dengan penuh gaya, mengibarkan aturan yang sudah mereka tabrak sendiri, seakan semua orang lupa sejarah yang baru berumur tujuh tahun. Apakah mereka pikir dunia ini terdiri dari manusia-manusia pelupa yang mudah ditipu dengan jargon hukum internasional?
Ironinya semakin terasa jika kita ingat: snapback itu diciptakan sebagai jalan darurat, mekanisme veto-proof yang memungkinkan kembalinya sanksi jika Iran terbukti melanggar kesepakatan. Tetapi, siapa sebenarnya yang pertama melanggar? Bukankah Amerika Serikat yang memutuskan keluar, disusul oleh ketidakmampuan Eropa sendiri untuk memenuhi kewajiban mereka—dari perdagangan hingga perlindungan ekonomi? Apakah adil jika pihak yang gagal menepati janji justru merasa berhak menjadi hakim? Saya rasa, yang kita lihat bukan lagi diplomasi, melainkan seni berpura-pura.
Iran, melalui wakil menteri luar negerinya, Kazem Gharibabadi, dengan lantang menolak legalitas langkah ini. Mereka menegaskan bahwa Eropa dan Amerika sudah kehilangan “standing” untuk memicu mekanisme tersebut. Dan sulit untuk tidak setuju. Bagaimana mungkin seseorang yang keluar dari meja perundingan, membalikkan meja, lalu merusak kursi, tiba-tiba kembali dan berkata: aturan permainan masih berlaku? Itu seperti seorang pedagang yang membatalkan kontrak jual-beli, tapi kemudian menuntut pembeli karena dianggap tak membayar penuh. Konyol, tapi nyata.
Yang lebih ironis, langkah Eropa ini muncul bertepatan dengan kembalinya para inspektur IAEA ke Iran. Setelah serangan Amerika dan Israel menghantam fasilitas nuklir pada Juni, kerja sama dengan IAEA mulai dirintis kembali. Bahkan, ada momen simbolis: penggantian batang bahan bakar di reaktor Bushehr dengan supervisi Rusia, disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Sebuah langkah yang memperlihatkan bahwa Iran, meski dikepung tekanan, masih membuka pintu dialog teknis. Tapi E3 tampaknya tidak peduli. Mereka memilih memukul pintu yang baru saja terbuka.
Kita semua tahu, IAEA bukan sekadar badan teknis. Di mata Iran, lembaga itu sering tampak seperti agen ganda, dengan bayang-bayang intelijen yang terlalu dekat dengan Israel. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar: penggunaan sistem Palantir MOSAIC, yang memang berkolaborasi dengan entitas keamanan Barat, memberi alasan bagi Iran untuk merasa bahwa pengawasan berubah menjadi peretasan yang dilegalkan. Jika kepercayaan sudah keropos, seharusnya Eropa justru mencari cara untuk menenun kembali benang-benang yang rapuh. Tapi yang terjadi sebaliknya: snapback menjadi gunting yang siap memutus.
Ada satu hal yang terasa menyakitkan: seolah Eropa hidup di dunia paralel, di mana hukum internasional adalah mainan privat. Mereka bisa menggunakan pasal ketika menguntungkan, lalu mengabaikannya ketika menyulitkan. Apakah ini hukum, atau sekadar politik yang memakai jas hukum? Bagi Iran, jelas ini bukan sekadar soal sanksi. Ini soal martabat, soal bagaimana sebuah bangsa dipaksa tunduk dengan aturan yang bahkan tidak lagi dipegang teguh oleh penciptanya sendiri. Dan bagi kita yang hidup di negara berkembang, pengalaman ini begitu akrab. Bukankah kita sering menyaksikan kontrak atau perjanjian internasional hanya berlaku ketika sesuai dengan kepentingan pihak kuat, tapi tiba-tiba menjadi fleksibel atau dilupakan ketika tidak lagi menguntungkan mereka?
The Soufan Center, think tank yang bermarkas di New York, menulis dengan lugas: tujuan Amerika dan Eropa adalah menjaga Iran tetap lemah, agar tak mampu memulihkan program nuklirnya. Bahkan lebih jauh, melemahkan ekonominya hingga rakyat bangkit melawan pemerintahnya. Dengan kata lain, sanksi bukan sekadar soal nuklir, melainkan strategi mengguncang legitimasi politik dari dalam. Dan di sinilah kita menemukan absurditas terbesar: apakah benar menciptakan penderitaan ekonomi bagi jutaan rakyat sipil akan melahirkan demokrasi dan stabilitas? Atau justru memperkuat narasi pemerintah Iran bahwa mereka adalah korban kezaliman global?
Saya kira jawabannya jelas. Sejarah membuktikan, tekanan eksternal justru sering kali memperkokoh rezim yang ditargetkan. Rakyat mungkin menderita, tapi penderitaan itu diarahkan kepada musuh eksternal, bukan kepada pemerintah mereka sendiri. Iran tahu itu, Barat pun sebenarnya tahu. Tapi entah mengapa, E3 memilih mengulang pola lama, seakan berharap hasil yang berbeda. Bukankah Einstein pernah berkata, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang sambil berharap hasil berbeda? Maka, kegilaan politik internasional ini kini terpampang di meja Dewan Keamanan.
Lebih ironis lagi, mekanisme snapback ini sendiri punya tenggat. Pada 18 Oktober, peluang untuk memakainya hilang, karena setelah itu Rusia dan Cina siap menggunakan hak veto. Maka langkah E3 tampak seperti balapan melawan waktu, bukan demi menjaga hukum, melainkan demi memastikan sanksi bisa diterapkan sebelum pintu tertutup. Jadi, siapa sebenarnya yang main politik di sini? Iran yang mencoba tetap bertahan dalam kerangka kerja IAEA, atau Eropa yang mendadak merasa perlu menegakkan hukum yang sudah lama mereka langgar sendiri?
Dari sini kita bisa menarik benang merah yang pahit: perjanjian internasional, dalam praktiknya, sering kali hanyalah alat dominasi. Ketika menguntungkan, ia dikumandangkan bak kitab suci; ketika merugikan, ia ditinggalkan begitu saja. JCPOA 2015, yang dulu dielu-elukan sebagai kemenangan diplomasi multilateral, kini tinggal reruntuhan yang dijadikan alasan untuk sanksi sepihak. Dan kita diminta percaya bahwa ini demi stabilitas dunia? Rasanya, logika ini lebih cocok masuk buku satir daripada buku hukum internasional.
Saya membayangkan analoginya begini: bayangkan kita ikut arisan kampung. Ada satu anggota yang tiba-tiba kabur, tak mau setor iuran, bahkan menjelek-jelekkan penyelenggara. Lalu, setelah beberapa bulan, ia datang lagi dan berkata, “Hei, aturan arisan masih berlaku, kalian yang salah kalau tak ikut cara saya.” Kira-kira bagaimana reaksi kita? Tentu saja sinis, bahkan marah. Begitulah rasanya melihat E3 dengan wajah tanpa malu memicu snapback.
Pada akhirnya, kita harus bertanya: apa arti sebuah kesepakatan jika hanya digunakan sebagai tongkat untuk memukul pihak lain, tanpa ada niat menepati kewajiban sendiri? Apa makna hukum internasional jika hanya berlaku bagi yang lemah, sementara yang kuat bebas keluar masuk tanpa konsekuensi? Dunia mungkin tidak sepenuhnya bodoh. Dunia hanya terlalu sering dipaksa untuk berpura-pura percaya pada dongeng keadilan yang disusun oleh mereka yang memegang pena.
Dan karena itu, langkah E3 kali ini bukan hanya sekadar soal Iran. Ia adalah cermin dari krisis kredibilitas hukum internasional itu sendiri. Setiap bangsa di Global South, termasuk kita di Indonesia, seharusnya membaca pesan ini: jika sebuah perjanjian tidak lagi berlandaskan kesetaraan, maka ia hanyalah rantai baru dalam bentuk yang lebih sopan.
Maka, jika Eropa beranggapan dunia akan diam saja, mereka salah besar. Ketelanjangan arogansi itu terlalu jelas untuk ditutupi. Dan kita berhak, setidaknya, untuk menyebutnya apa adanya: sebuah permainan hukum yang kehilangan jiwa, sebuah diplomasi yang berubah menjadi sandiwara, sebuah kesepakatan yang dijadikan senjata. Ya, inilah snapback, wajah telanjang arogansi E3 terhadap Iran.









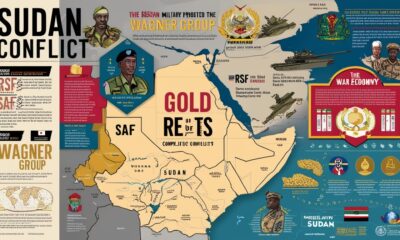

Pingback: Si Vis Pacem Para Bellum: Strategi Iran Hadapi Tekanan Barat