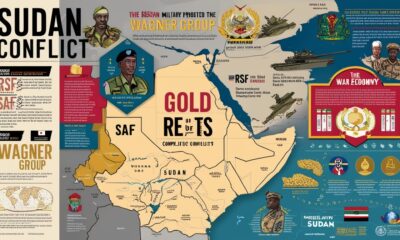Opini
Iran, Nuklir, dan Poros Timur yang Makin Solid

Ketika juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengumumkan bahwa Rusia, China, dan Iran akan menggelar pertemuan trilateral untuk membahas program nuklir Teheran, dunia hanya menoleh sejenak. Tetapi di balik berita yang tampak rutin itu, ada kegelisahan yang lebih dalam—sebuah kegentingan yang perlahan menggumpal. Ini bukan lagi sekadar urusan pengayaan uranium atau pencabutan sanksi. Ini tentang siapa yang berhak menentukan batas ambisi sebuah negara. Ini tentang siapa yang diizinkan tumbuh, dan siapa yang harus dibonsai.
Baghaei menyebut bahwa pertemuan itu juga akan membahas ancaman Inggris, Prancis, dan Jerman yang hendak mengaktifkan kembali sanksi PBB terhadap Iran. Ancaman ini, seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, bisa menjadi kenyataan secepat bulan depan jika tak ada “kemajuan berarti” dalam pembatasan aktivitas nuklir Iran. Tetapi apa yang dimaksud dengan “kemajuan berarti”? Dan siapa yang berhak menentukannya? Ketika negara-negara Barat berbicara soal non-proliferasi dan stabilitas global, sering kali yang mereka maksud adalah menjaga tatanan yang mereka bentuk sendiri.
Rusia dan China masih menjadi bagian dari kesepakatan nuklir 2015, JCPOA, yang dulu dipuji sebagai tonggak diplomasi multilateral. Kini, dua negara tersebut menjadi sandaran strategis bagi Iran dalam menghadapi tekanan Barat. Dalam penuturan Baghaei, konsultasi antara Iran dengan Rusia dan China berjalan baik. Ia menegaskan bahwa secara hukum dan logika, tidak ada dasar untuk mengaktifkan kembali sanksi yang telah dicabut. Pernyataan ini tentu bukan hanya argumen hukum, tetapi juga ekspresi frustrasi atas janji-janji diplomasi yang patah di tengah jalan.
Apa yang dilihat Iran bukan sekadar kegagalan teknis perjanjian, tetapi penghianatan terhadap prinsip timbal balik. Ketika AS secara sepihak keluar dari JCPOA pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi maksimum, Eropa tidak benar-benar mampu—atau mungkin tidak sungguh-sungguh—menyelamatkan kesepakatan. Iran menahan diri selama bertahun-tahun sebelum akhirnya juga mundur dari sebagian komitmennya, termasuk membatasi kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Hubungan yang dulu dibangun atas dasar transparansi dan kepercayaan kini berubah menjadi saling tuduh dan penuh kecurigaan.
Iran menuduh IAEA menerbitkan laporan yang berat sebelah—laporan yang dianggap menjadi dalih zionis untuk melancarkan serangan militer 12 hari terhadap Iran. Ini bukan tuduhan kecil. Jika benar, itu berarti sebuah lembaga internasional digunakan untuk membenarkan perang. Dan jika tuduhan itu salah, maka sikap Iran menjadi cermin dari kepanikan diplomatik. Dalam situasi ini, kebenaran bukan hanya soal data, tetapi juga soal siapa yang membingkai narasi. Di tengah kebisingan retorika global, siapa yang bisa memastikan bahwa laporan IAEA bersih dari tekanan politik?
AS sendiri tetap menjadi aktor sentral dalam drama ini, meski Iran menyatakan tak punya rencana berbicara dengan Washington. Posisi Iran jelas: mereka menolak tuntutan AS untuk sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium. Washington menyebut kapasitas itu sebagai ancaman terhadap keamanan global, potensi jalan menuju senjata nuklir. Teheran membantah keras—menyatakan bahwa pengayaan uranium adalah hak mereka untuk memenuhi kebutuhan energi sipil. Ini semacam pertarungan ideologis antara kedaulatan nasional dan kekhawatiran kolektif. Tetapi benarkah kekhawatiran itu netral?
Rusia dan China mengambil posisi yang relatif konsisten: bahwa masalah ini hanya bisa diselesaikan lewat jalur politik dan diplomatik. Di satu sisi, ini menegaskan pentingnya diplomasi multilateral. Tapi di sisi lain, juga menunjukkan bahwa arena diplomatik telah menjadi gelanggang geopolitik baru antara Barat dan Timur. Negara-negara seperti Indonesia bisa belajar dari situasi ini: bahwa dalam percaturan global, stabilitas hukum internasional sangat rentan terhadap dinamika kekuasaan. Tidak cukup hanya dengan menjadi netral atau menyerukan perdamaian dari kejauhan.
Bagi Indonesia, yang selama ini mengedepankan prinsip nonblok dan penghormatan terhadap hukum internasional, krisis nuklir Iran menyimpan banyak pelajaran. Ketika satu negara dikepung oleh tuduhan dan ancaman sanksi, sementara pihak lain—yang jelas-jelas memiliki senjata nuklir seperti Israel—tidak pernah disentuh, pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang bersalah, tetapi siapa yang dilindungi oleh sistem internasional. Di sinilah letak absurditas yang menggugah kegelisahan itu. Dunia seolah buta terhadap ketimpangan, tetapi peka terhadap siapa yang melawan ketimpangan itu.
Pertemuan antara Iran dan negara-negara Eropa dijadwalkan berlangsung di Istanbul. Tidak di Jenewa, bukan di New York. Mungkin ini simbol bahwa pusat-pusat diplomasi pun mulai bergeser, bahwa jalur negosiasi baru tak harus selalu melalui pintu Barat. Tapi sejauh mana itu bisa mengubah hasil akhir? Jika ujungnya tetap sanksi dan tekanan, maka diplomasi hanya jadi jeda dari konflik yang tak pernah benar-benar selesai. Ironisnya, justru di tengah upaya diplomasi inilah serangan dan ancaman terus terjadi.
Banyak pihak bertanya, mengapa Iran terus bersikukuh mempertahankan program pengayaan uraniumnya? Jawabannya, sebagian karena kebutuhan energi. Tapi sebagian lainnya karena harga diri. Dalam benak pemimpin Iran—dan sebagian rakyatnya—mengalah berarti tunduk. Dan tunduk berarti kehilangan martabat nasional yang telah diperjuangkan di tengah blokade dan ancaman selama puluhan tahun. Kita bisa saja tidak sepakat dengan semua langkah Iran, tetapi sulit untuk mengabaikan bahwa resistensi mereka tumbuh dari luka kolektif yang panjang: invasi, sabotase, embargo, dan isolasi.
Tentu saja, ini bukan cerita tentang pahlawan dan penjahat. Ini cerita tentang kekuasaan dan bagaimana ia digunakan. Dalam sejarah politik internasional, klaim tentang keamanan global sering kali menjadi dalih untuk mempertahankan dominasi lama. Siapa yang berhak punya senjata? Siapa yang harus diawasi? Siapa yang bebas menentukan jalan industrinya sendiri, dan siapa yang harus meminta izin? Ini bukan hanya pertanyaan teknis, melainkan refleksi mendalam tentang bagaimana dunia ini diatur, dan untuk siapa.
Saat kita di Indonesia menyaksikan semua ini dari layar gawai atau berita-berita pendek di media sosial, ada baiknya kita tidak sekadar menyimak dari jarak aman. Dunia yang sedang berubah ini akan berimbas juga pada kita. Dalam diplomasi energi, dalam harga minyak, dalam keamanan kawasan. Indonesia, yang tengah mencari jalur energi alternatif, bisa saja terjebak dalam dinamika sanksi global jika tidak cermat membaca peta geopolitik baru. Maka memahami Iran hari ini bukan soal solidaritas, tapi juga soal kesiapan masa depan.
Krisis nuklir Iran adalah cermin yang menantang dunia: apakah kita sungguh-sungguh menghormati hukum dan kesetaraan, atau hanya melestarikan ketimpangan yang dibungkus diplomasi. Pertemuan di Teheran, Moskow, Beijing, dan Istanbul bukan hanya peristiwa diplomatik, tetapi juga ujian atas masa depan sistem internasional. Kita, sebagai bagian dari komunitas global, tak bisa terus menghindari pertanyaan itu. Dan barangkali, pertanyaan yang lebih besar: jika dunia tak adil, lalu kepada siapa kita bisa berharap?