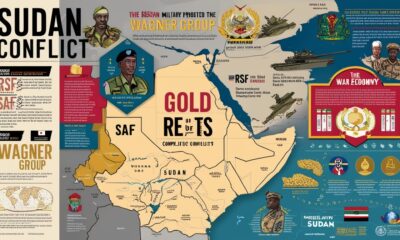Opini
Radikalisme Digital dan Jejak ISIS yang Masih Mengintai

Kabut tipis menyelimuti layar ponsel, menyamarkan pesan-pesan berbahaya yang masuk diam-diam ke grup WhatsApp. Di balik riuh notifikasi, tersembunyi narasi propaganda yang menggoda—ajakan terselubung yang perlahan menggerogoti kedamaian. Pada 24 Mei 2025, Densus 88 Antiteror Polri menangkap seorang pelajar SMA berusia 18 tahun, MAS, di Gowa, Sulawesi Selatan. Ia diduga menyebarkan ideologi ISIS melalui grup daring bernama “Daulah Islamiah.” Kasus ini menjadi alarm keras: bagaimana mungkin seorang remaja, yang seharusnya sibuk dengan pelajaran dan impian masa depan, terjerat dalam pusaran jaringan radikalisme digital?
Sejumlah media seperti Okezone, Detik, dan Tempo melaporkan bagaimana penangkapan ini menunjukkan wajah baru ancaman teror: bukan ledakan di ruang publik, tapi konten ekstremis yang menyusup diam-diam ke dalam pikiran lewat layar ponsel. MAS ditangkap di depan rumahnya, di Jalan SD Daeng Emba, Kelurahan Samata, sekitar pukul 17.30 WITA, usai membeli air galon. Sosoknya tak menonjol, tampak religius, aktif beribadah, bahkan mengajar di rumah tahfidz. Tapi di balik keteduhan penampilannya, tersembunyi peran penting: ia diduga sebagai pengelola utama kanal digital penyebar ideologi kekerasan.
AKBP Mayndra Eka Wardhana, PPID Densus 88, menyatakan bahwa MAS aktif membagikan konten dukungan terhadap ISIS, mulai dari video, gambar, hingga rekaman suara dan tulisan yang mengandung ajakan kekerasan, termasuk seruan bom bunuh diri. Barang bukti yang diamankan—ponsel Oppo A3X dan sepeda motor Honda Blade—terkesan biasa. Namun justru dari perangkat sederhana ini, ideologi berbahaya disebarkan, menunjukkan betapa dunia digital telah menjadi medan baru radikalisasi.
Laporan Global Terrorism Index (GTI) 2025 memperkuat kekhawatiran tersebut. Indonesia memang mengalami penurunan peringkat ke posisi 30 dengan skor 4,17, menandakan turunnya dampak teror secara umum. Namun, ancaman laten tetap nyata. Meski ISIS telah kehilangan wilayah kekuasaannya, GTI mencatat bahwa kelompok ini tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan sepanjang 2024, dengan 1.805 korban jiwa di 22 negara. Di Indonesia, tak ada korban akibat aksi teror tahun lalu. Tapi aktivitas seperti yang dilakukan MAS membuktikan bahwa ideologi ekstremis belum mati—ia hanya berganti bentuk dan berpindah ruang: dari jalanan ke dunia maya.
Grup WhatsApp “Daulah Islamiah” yang dibentuk sejak Desember 2024, digunakan untuk mendiskusikan hal-hal yang mengkhawatirkan, seperti hukum bom bunuh diri dan justifikasi kekerasan. Yang lebih mengusik hati adalah kesaksian ibunya, Siti Khadijah. Ia menggambarkan MAS sebagai anak pendiam, jarang keluar rumah, dan hanya pergi ke masjid atau membeli keperluan. MAS juga mengajar di rumah tahfidz—aktivitas yang sepintas mulia. Kini semua hal itu menjadi pertanyaan besar: apakah MAS radikal karena lingkungan, ataukah proses itu terjadi sendirian di ruang pribadinya?
Fenomena ini menggambarkan pola baru yang disebut para peneliti sebagai Terorisme 4.0—radikalisasi digital secara individual. MAS adalah contoh nyata dari aktor tunggal (lone wolf) yang teradikalisasi di balik layar, tanpa harus bergabung secara fisik dengan jaringan teror. GTI 2025 mencatat satu dari lima tersangka teroris di negara-negara Barat kini adalah remaja di bawah usia 18 tahun. Indonesia tidak kebal. Platform seperti WhatsApp dan Telegram—dengan sistem enkripsi yang kuat—menjadi ruang subur untuk menyebarkan ideologi ekstremis secara tersembunyi.
Lalu, mengapa seorang remaja dari Gowa—daerah yang relatif tenang dan jauh dari pusat konflik—bisa begitu mudah terpikat pada ideologi penuh kekerasan? Jawabannya bisa terletak pada kombinasi ketimpangan sosial, ekonomi, dan minimnya akses terhadap literasi digital. GTI menekankan bahwa ketidaksetaraan merupakan salah satu pendorong utama radikalisasi. Meskipun latar belakang ekonomi keluarga MAS tidak dipaparkan secara rinci, posisinya sebagai pelajar dari luar kota besar menunjukkan kerentanan tertentu. Survei Kompas 2021 menunjukkan bahwa 40,6% responden menyebut internet sebagai faktor utama radikalisasi, diikuti tekanan ekonomi sebesar 26,5%.
Keberhasilan Densus 88 menangkap MAS patut diapresiasi. Namun, penangkapan ini juga memperlihatkan tantangan besar dalam menghadapi ancaman yang terus bermetamorfosis. Teknologi yang digunakan para pelaku teror—ponsel, aplikasi perpesanan instan, media sosial—mudah diakses dan murah. Sementara itu, sistem pengawasan negara menuntut perangkat canggih dan sumber daya besar. Dalam Rakernis Densus 88 April 2025, diakui bahwa pendekatan berbasis big data dan biometrik belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan SDM.
Upaya kontra-radikalisasi berbasis narasi positif pun belum sepenuhnya efektif. Densus 88 bekerja sama dengan NU, Muhammadiyah, dan lembaga keagamaan lain untuk menyebarkan pesan moderasi. Namun narasi damai sering kalah menarik dibandingkan propaganda ekstrem yang dikemas dramatis dan emosional. Bagi remaja seperti MAS, video pendek dengan semangat jihad bisa lebih memikat daripada ceramah panjang penuh istilah teologis yang kaku.
Program literasi digital yang digagas BNPT memang berjalan, tapi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah terpencil seperti Gowa. Tanpa pemahaman kritis terhadap cara kerja propaganda digital, generasi muda mudah menjadi sasaran empuk narasi kebencian yang tersebar tanpa saringan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Densus 88 bekerja sama dengan platform digital seperti Meta dan Google dalam memblokir ribuan konten ekstremis. Namun laporan Kompas.id menunjukkan bahwa upaya ini belum cukup. Aplikasi terenkripsi seperti WhatsApp tetap sulit dijangkau tanpa pelanggaran privasi pengguna. Regulasi seperti Pasal 13A UU No. 5 Tahun 2018 memang memberi dasar hukum penindakan, tapi perkembangan teknologi menuntut respons hukum yang lebih adaptif.
Di balik semua itu, kisah MAS juga menghadirkan sisi kemanusiaan yang mengharukan. Ibunya menyebut anaknya sebagai pribadi berakhlak baik. Ketua RW setempat pun tak mencurigai apa pun. Ini menggambarkan bahwa radikalisasi bisa terjadi tanpa gejala mencolok, bahkan di lingkungan yang tampaknya normal dan religius.
Kasus MAS menjadi pengingat bahwa medan perang ideologis kini bukan hanya di tempat-tempat konflik, tetapi juga di ruang privat seorang remaja. Gowa mungkin jauh dari pertempuran, tetapi ideologi ekstrem menembus jarak lewat sinyal internet. Densus 88 telah menangkap satu pelaku, namun tugas yang lebih besar masih terbentang: membentengi generasi muda dari paparan ekstremisme digital.
Ini bukan sekadar tugas aparat. Ini adalah tanggung jawab bersama: orang tua, guru, pemuka agama, media, dan setiap warga yang peduli akan masa depan bangsa.
Sumber:
- https://www.tempo.co/hukum/densus-88-tangkap-seorang-terduga-teroris-di-gowa-1543290
- https://news.detik.com/berita/d-7931335/terduga-teroris-penyebar-konten-isis-ditangkap-di-gowa-usianya-18-tahun
- https://news.detik.com/berita/d-7931594/densus-88-ungkap-remaja-terduga-teroris-aktif-di-grup-bahas-bom-bunuh-diri
- https://nasional.okezone.com/read/2025/05/25/337/3141836/pelajar-sma-ajak-bom-tempat-ibadah-densus-88-sita-sejumlah-barang-bukti?page=2
- https://vichara.id/opini/terorisme-4-0-ancaman-digital-mengintai-indonesia/