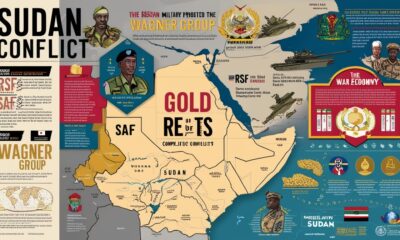Opini
Normalisasi Suriah-Israel di Tengah Krisis Dalam Negeri

Di jalan-jalan Aleppo yang masih menyimpan debu perang, darah belum kering sepenuhnya, dan suara tangisan anak-anak belum reda, elit politik di Damaskus justru sibuk memikirkan agenda yang jauh dari perut rakyat. Ironisnya, bukan soal roti, obat, atau keamanan di malam hari yang gelap tanpa listrik. Melainkan soal pertemuan rahasia, negosiasi penuh teka-teki, dan wacana yang digadang-gadang sebagai *Normalisasi Suriah-Israel*. Begitu absurdnya, hingga kita bertanya: apakah lembaran sejarah sedang diputar balik, atau sekadar sandiwara yang dimainkan untuk meninabobokan khalayak?
Kita tahu, presiden transisi Ahmad al-Sharaa berkali-kali menyangkal. Katanya, tidak ada agenda normalisasi dengan Israel. Katanya, Damaskus hanya mengutamakan kepentingan nasional. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Pertemuan antara Menlu Suriah Asaad al-Shaibani dengan Ron Dermer, menteri urusan strategis Israel, terus berlangsung—baik di Prancis, di forum tertutup, maupun dalam bayang-bayang mediasi Amerika. Kalau ini bukan normalisasi, lalu apa? Sekadar kencan politik dengan tabir kerahasiaan? Atau pemanasan sebelum akad yang lebih resmi?
Sementara itu, laporan dari Syrian Observatory for Human Rights mencatat 280 tindak kriminal sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024 hingga September 2025. Tiga ratus lebih nyawa melayang, sebagian besar laki-laki, tetapi juga ada puluhan perempuan dan anak-anak. Angka-angka itu bukan sekadar statistik dingin. Itu adalah potret getir dari sebuah negeri yang kehilangan pegangan, di mana hukum tumpul, aparat tak berdaya, dan rakyat dibiarkan menghadapi maut tanpa perlindungan.
Bandingkan dua realitas ini: di luar negeri, Suriah berbincang tentang perjanjian non-agresi dengan Tel Aviv; di dalam negeri, Suriah gagal menjamin keselamatan warganya di Daraa, Hama, atau Sweida. Kontras yang begitu tajam hingga terasa seperti satire murahan. Kita mendengar pejabat bicara tentang “kedaulatan negara” di meja perundingan, padahal di gang-gang sempit Damaskus orang bisa terbunuh tanpa pelaku pernah ditangkap. Kedaulatan macam apa yang hanya berlaku di dokumen diplomasi, tapi tak pernah menyentuh daging rakyatnya sendiri?
Saya rasa, inilah paradoks rezim transisi: berusaha membangun legitimasi lewat pengakuan eksternal, sembari abai terhadap legitimasi yang lebih nyata—yakni rasa aman di dada setiap warga. Normalisasi Suriah-Israel, jika benar-benar terjadi, mungkin menjanjikan “perlindungan” dari ancaman luar, terutama keberadaan Iran dan Hizbullah di Suriah selatan. Tetapi mari kita jujur, ancaman paling nyata bagi rakyat hari ini bukanlah rudal Tel Aviv, melainkan pisau perampok di jalanan Homs, atau peluru nyasar dalam pertikaian lokal di Deir Ezzor.
Mengapa elit politik lebih peduli pada keamanan perbatasan ketimbang keamanan dapur rakyat? Jawabannya barangkali sederhana: diplomasi dengan Israel membuka pintu bagi restu Amerika, dan restu itu bisa berarti bantuan dana, pengakuan internasional, dan jaminan bertahan hidup bagi elit yang kini rapuh. Dengan kata lain, ini adalah politik bertahan hidup, bukan politik melayani rakyat.
Kita semua tahu, normalisasi bukanlah istilah netral. Ia sarat makna historis, terutama di Timur Tengah. Negara-negara Arab yang lebih dulu menandatangani perjanjian damai dengan Israel sering mendapat label “pengkhianat” oleh sebagian kalangan. Suriah selama ini berdiri di barisan depan penolakan. Maka jika hari ini Damaskus perlahan bergeser, itu bukan hanya perubahan kebijakan luar negeri. Itu adalah pergeseran identitas, sebuah renegoisasi dengan sejarah panjang perlawanan. Dan perubahan ini dilakukan justru ketika rakyat sendiri masih berdarah-darah di tanahnya sendiri.
Ada ironi lain yang tak kalah pahit. Salah satu topik dalam perundingan adalah menjadikan wilayah perbatasan sebagai zona demiliterisasi, bahkan tanpa kehadiran tentara Suriah sendiri. Sebagai gantinya, hanya pasukan ringan yang bertugas menjaga ketertiban. Bayangkan, sebuah negara rela menanggalkan kekuatan militernya di tanahnya sendiri, demi menenangkan musuh lamanya. Bukankah ini serupa menyerahkan pagar rumah kepada tetangga yang selama ini justru kerap merampok ladang kita?
Dalam konteks Indonesia, hal ini bisa dianalogikan begini: bayangkan jika Jakarta sibuk berunding dengan negara lain soal keamanan Natuna, tapi di Jawa dan Sumatra orang setiap hari dibunuh tanpa keadilan. Wajar kalau rakyat mempertanyakan prioritas pemerintah. Kita bisa menoleransi diplomasi, bisa memahami pragmatisme, tapi sulit menerima jika semua itu dilakukan di atas tubuh rakyat yang terluka.
Saya tidak menutup mata, Suriah tentu berada dalam tekanan. Perang panjang, sanksi ekonomi, fragmentasi sosial—semuanya membuat negeri itu ringkih. Tapi justru di tengah kerentanan itulah seharusnya fokus diarahkan ke dalam, bukan ke luar. Tanpa keamanan domestik, setiap perjanjian internasional hanya akan menjadi kertas kosong. Dan tanpa rasa percaya rakyat, setiap janji elit hanya terdengar seperti gema kosong di aula konferensi.
Apa yang kita lihat hari ini adalah gejala klasik: pemerintah transisi mencari jalan pintas lewat diplomasi internasional, berharap dunia menganggap Suriah telah stabil, padahal kenyataan di lapangan adalah sebaliknya. Inilah absurditas yang membuat kita ingin tertawa getir: normalisasi dengan Israel digadang sebagai solusi, sementara normalisasi kehidupan sehari-hari rakyat Suriah—roti yang cukup, jalan yang aman, sekolah yang damai—justru tak kunjung diperhatikan.
Kita mungkin bertanya, bagaimana sejarah akan mencatat momen ini? Apakah sebagai langkah pragmatis yang menyelamatkan Suriah dari isolasi, atau sebagai awal dari penyerahan jati diri? Saya cenderung percaya sejarah akan mencatatnya sebagai titik di mana elit politik lebih memilih berdamai dengan musuh lama daripada berdamai dengan rakyatnya sendiri.
Pada akhirnya, Normalisasi Suriah-Israel bukan sekadar soal diplomasi. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah rapuh rezim transisi. Cermin yang menunjukkan betapa mudahnya kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan geopolitik. Cermin yang mengingatkan kita bahwa kedaulatan sejati bukan di meja perundingan, melainkan di pasar-pasar, sekolah, dan rumah warga yang aman. Selama kedaulatan itu tidak hadir di sana, semua pembicaraan di Paris hanyalah ilusi belaka.
Sumber: