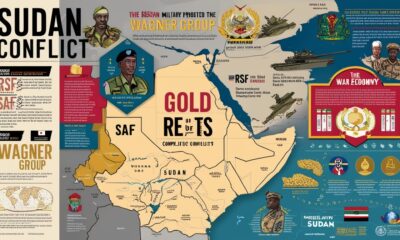Opini
Minoritas Suriah Digencet: Gereja Jadi Sasaran Teror

Sebuah ledakan mengguncang Gereja Mar Elias di Dweila, Damaskus, pada Minggu yang seharusnya penuh damai, merenggut lebih dari 20 nyawa jemaat yang sedang berdoa. Saksi mata, dikutip RIA Novosti, menyebutnya serangan yang disengaja: “Seorang teroris meledakkan bom di gereja saat ibadah. Banyak tewas.” Foto-foto yang dirilis SANA memperlihatkan dinding hangus, bangku gereja yang hancur, dan lantai berlumur darah—gambaran kengerian yang sulit dilupakan. Saat umat Kristen merayakan Hari Raya Semua Orang Suci Antiokhia, teror kembali menghantam komunitas yang sudah lama hidup dalam ketakutan. Saya menulis ini sebagai pengamat yang prihatin, mencoba memahami mengapa dunia seolah menutup mata pada penderitaan minoritas Suriah.
Suriah kini berada di persimpangan yang rapuh. Pergantian rezim dari Bashar al-Assad ke Ahmad al-Sharaa pada akhir 2024 sempat menjanjikan angin baru untuk rekonsiliasi nasional, tetapi kenyataan berkata lain. Al-Sharaa, mantan pemimpin Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) yang pernah berafiliasi dengan al-Qaeda, kini berjuang meyakinkan dunia bahwa ia mampu melindungi semua warga—termasuk kelompok minoritas seperti Kristen dan Alawit. Al Mayadeen melaporkan bahwa ISIS mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman gereja ini, dengan pelaku meledakkan rompi bom di tengah jemaat. Dan ini bukan insiden tunggal. Pada Maret 2025, lebih dari 1.300 warga sipil—kebanyakan Alawit dan Kristen—tewas dalam gelombang kekerasan yang terkait dengan faksi-faksi bersenjata yang bersekutu longgar dengan pemerintahan transisi.
Ironisnya, insiden-insiden ini nyaris luput dari sorotan internasional, seolah dunia hanya mencatatnya sebagai statistik dingin dalam laporan tahunan. Pemerintah Suriah meluncurkan penyelidikan resmi, tetapi banyak pengamat internasional menilainya tidak transparan dan jauh dari kata memadai. Untuk komunitas minoritas, hasil penyelidikan yang kabur sama saja dengan pengabaian terhadap hak-hak dasar mereka.
Bayangkan hidup sebagai minoritas di Suriah saat ini. Di masa Assad, meski banyak tuduhan represi dan otoritarianisme, komunitas Kristen kerap mendapat perlindungan strategis karena aliansi politik tertentu. Kini, mereka merasa ditinggalkan. Gereja, tempat suci yang seharusnya menawarkan ketenangan, justru menjadi sasaran teror. Bagaimana rasanya berdoa dalam suasana was-was, mengetahui bahwa pintu gereja bisa jadi gerbang menuju kematian?
Di Indonesia, kita punya kenangan yang tak kalah pahit. Pengeboman Gereja Oikumene di Samarinda pada 2016, yang menewaskan seorang balita, masih membekas. Meski konteksnya berbeda, rasa takut yang muncul akibat kekerasan terhadap tempat ibadah sama menyayatnya. Perasaan bahwa tempat paling aman pun tak lagi menjamin keselamatan kini menjadi pengalaman global umat beragama yang hidup dalam bayang-bayang ekstremisme.
Pemerintah transisi di bawah Al-Sharaa menghadapi kecurigaan yang bukan hanya soal masa lalu. Dalam upaya yang diklaim sebagai langkah diplomasi, ia diketahui membuka dialog rahasia dengan Israel, dimediasi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Teluk, menurut laporan Al Mayadeen. Bagi banyak warga Suriah dan sekutunya seperti Hizbullah, Israel bukan sekadar lawan geopolitik, melainkan simbol penjajahan dan kolonialisme yang menyakitkan. Maka, langkah dialog itu dianggap sebagai kompromi yang tak bisa diterima—bahkan disebut sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dasar perjuangan Suriah.
Hizbullah secara terbuka menyebut pengeboman gereja Mar Elias sebagai “kejahatan keji” yang didukung oleh “poros Amerika-Zionis.” Di dalam negeri, janji Al-Sharaa untuk melakukan penyelidikan atas insiden tersebut terdengar hambar dan tak menghasilkan kepercayaan baru. Ketika kekerasan meningkat dan pelaku tidak pernah benar-benar ditangkap atau diadili, apa artinya sebuah komitmen?
Dunia internasional pun menunjukkan wajah yang ragu-ragu. Amerika Serikat menangguhkan Caesar Act selama enam bulan, sementara Uni Eropa melonggarkan sanksi terhadap Suriah. Dalihnya adalah demi stabilitas ekonomi dan penguatan rekonsiliasi. Namun, banyak yang menilai langkah ini sebagai kompromi moral yang berbahaya—karena dilakukan tanpa syarat perlindungan hak asasi manusia dan keamanan kelompok minoritas.
Geir Pedersen, Utusan Khusus PBB untuk Suriah, menyampaikan seruan moral: “Semua pihak wajib melindungi warga sipil dan tempat ibadah tanpa kecuali.” Tapi tanpa tindakan konkret, seruan ini hanya gema di ruang kosong. Solidaritas verbal tak menghentikan darah yang terus mengalir. Negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, dan Irak turut mengutuk serangan tersebut. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyebutnya “tindakan kriminal yang keji.” Tapi kecaman tak akan menyelamatkan satu pun nyawa, dan tentu tidak menjamin bahwa tragedi serupa tak akan terulang.
Suriah kini menjadi cermin dari kegagalan kolektif. Minoritas hidup dalam ketakutan konstan, tanpa jaminan keamanan dari negara atau dunia internasional. Kita di Indonesia pernah mengalami luka serupa—dari konflik Ambon hingga Poso, saat umat Muslim dan Kristen terjebak dalam spiral kekerasan sektarian. Perasaan ditinggalkan oleh negara, ketidakpastian hukum, dan trauma kolektif menyisakan luka yang bertahan puluhan tahun. Dalam skala dan konteks yang berbeda, Suriah hari ini memperlihatkan pola yang tak jauh beda.
Lantas mengapa dunia begitu lamban? Sanksi yang dilonggarkan mungkin membantu menstabilkan ekonomi Suriah, tapi tanpa tekanan politik dan diplomatik yang kuat untuk memastikan perlindungan terhadap kelompok minoritas, semua itu hanya menyelubungi kenyataan pahit dengan kepura-puraan. Apa yang benar-benar dibutuhkan adalah kehadiran nyata: investigasi independen dari lembaga internasional, atau bahkan pengawas kemanusiaan yang bisa memantau dan memberi laporan yang jujur. Tanpa itu, Gereja Mar Elias hanya akan menjadi satu dari sekian banyak bangunan suci yang diratakan oleh bom dan dilupakan sejarah.
Pertanyaan yang lebih dalam kini menggantung di udara: apa arti keadilan di tengah kekacauan seperti ini? Bagi jemaat di Dweila, keadilan bukan sekadar pernyataan belasungkawa atau komite penyelidik yang lamban. Keberadaan keadilan adalah ketika mereka bisa beribadah tanpa rasa takut, ketika pintu gereja kembali menjadi gerbang harapan, bukan ancaman. Bagi dunia, keadilan artinya bukan hanya menyalurkan bantuan kemanusiaan, tapi juga menuntut akuntabilitas dari pemerintahan Al-Sharaa—bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas keselamatan semua warganya, tanpa kecuali.
Di Indonesia, kita belajar bahwa perdamaian yang dibangun tanpa keadilan hanya akan menjadi genangan rapuh yang siap meledak kapan saja. Ingatlah bagaimana lambatnya penanganan konflik pasca-kerusuhan di Poso menyebabkan luka yang belum sepenuhnya pulih hingga kini. Suriah menghadapi situasi serupa. Negara itu butuh lebih dari sekadar kecaman; ia membutuhkan perhatian nyata, keberanian politik, dan upaya internasional yang tulus.
Tanpa itu semua, minoritas seperti jemaat Mar Elias akan terus hidup dalam bayang-bayang teror. Dunia hanya akan menjadi penonton diam, menyaksikan reruntuhan tempat suci sambil berdebat soal diplomasi. Dan sekali lagi kita diingatkan: perdamaian bukan cuma absennya perang, melainkan kehadiran keadilan—dan itu, sayangnya, masih jauh dari kenyataan di Suriah.
Sumber:
- https://english.almayadeen.net/news/politics/suicide-bombing-hits-church-in-damascus-during-sunday-mass
- https://english.almayadeen.net/news/politics/isis-claims-responsibility-for-damascus-church-bombing
- https://english.almayadeen.net/news/politics/un–regional-governments-condemn-damascus-church-bombing