Opini
Membungkam Saksi Gaza: 237 Jurnalis Tewas Dibunuh

Di sebuah tenda yang seharusnya menjadi ruang istirahat dan tempat menghela napas di tengah deru perang, empat jurnalis Palestina tewas diterjang ledakan. Anas al-Sharif, Mohammad Qraiqea, Mohammad Nawfal, dan Ibrahim Daher tidak sedang menyiapkan senjata, mereka sedang menyiapkan cerita. Ironinya, cerita yang tak pernah sampai. Ledakan itu bukan hanya memutus nyawa mereka, tapi juga memutus aliran informasi yang selama ini menjadi salah satu jalur terakhir dunia untuk mengintip realitas Gaza—realitas yang tidak pernah lolos dari sensor resmi dan framing politik.
Sebelum nyawanya direnggut, al-Sharif sudah lebih dulu diadili di ruang publik versi militer zionis. Tuduhan yang dilontarkan—bahwa ia anggota sayap bersenjata Hamas dan terlibat peluncuran roket—ditepis mentah-mentah oleh dirinya dan Al Jazeera. Tapi tuduhan itu bekerja seperti racun: menodai reputasi, merintangi simpati, dan memberi alasan “logis” bagi publik yang sudah disuguhi narasi tunggal. Tak ada pengadilan, tak ada bukti yang diuji, hanya ada label yang dipasang sebelum peluru dilepaskan.
Committee to Protect Journalists (CPJ) sudah mengendus polanya. Mereka menyebut ini bukan sekadar tuduhan kosong, tapi bagian dari kampanye fitnah militer yang biasanya jadi prolog menuju pembunuhan. Kasus ini tak berdiri sendiri. Sebelumnya, empat jurnalis Al Jazeera—Hamza Al Dahdouh, Ismail Al Ghoul, Rami Al Refee, dan Hossam Shabat—dibunuh dengan narasi pembenaran serupa: mereka disebut teroris. CPJ tak segan memakai kata yang sering dihindari oleh organisasi internasional: “murder”.
Angka 237 jurnalis Palestina tewas sejak 7 Oktober 2023 bukan statistik biasa. Itu adalah daftar panjang nama yang, seandainya masih hidup, mungkin akan mengisi layar berita, feed media sosial, atau kolom opini, dengan potret yang tidak akan pernah keluar dari kantor berita arus utama yang manis terhadap narasi penjajah. Ketika angka itu terus bertambah, sulit untuk menolak kesan bahwa ini bukan “dampak sampingan” perang, melainkan strategi terencana: membungkam saksi mata.
Kalau kebetulan Anda pernah ikut liputan di lapangan, Anda tahu betapa mustahilnya bekerja di wilayah konflik tanpa mengambil risiko. Tapi risiko yang diambil jurnalis di Gaza bukan risiko biasa. Mereka tidak hanya menghadapi bahaya karena berada di dekat pertempuran, mereka juga berada dalam daftar target. Bedanya tipis: di medan perang biasa, jurnalis bisa dilindungi oleh tanda “Press” di rompinya. Di Gaza, tanda itu kadang justru berfungsi sebagai target yang terang-benderang.
Tentu, pihak zionis selalu punya alasan. “Mereka teroris.” “Mereka menyamar.” “Mereka berbahaya.” Alasan yang terdengar seperti kaset kusut yang diputar ulang setiap kali ada kamera atau pena yang dihentikan paksa. Lucunya—atau tragisnya—klaim seperti ini sering dipercaya oleh publik yang tidak pernah menjejak tanah Gaza. Mereka percaya karena itulah yang mereka dapatkan dari berita yang lolos sensor, atau dari tur media yang dikawal ketat militer penjajah, lengkap dengan spot foto yang sudah diatur.
Di sini absurditasnya mulai terasa: jurnalis asing dilarang masuk Gaza kecuali lewat “kunjungan resmi” yang persis seperti open house developer perumahan—semua rapi, bersih, dan nyaman untuk dipamerkan, meski di luar pagar rumah itu ada kubangan lumpur. Media internasional yang seharusnya memeriksa fakta di lapangan malah disuguhi fakta versi satu pihak. Lalu publik internasional heran mengapa narasi Gaza begitu berbeda antara yang keluar dari mulut pejabat zionis dan yang keluar dari mulut warga Gaza.
Ini semua bukan skadar perang senjata, tapi juga perang narasi. Jika di medan tempur peluru menembus tubuh, di medan narasi peluru adalah kata-kata. Fitnah, framing, distorsi—semuanya diarahkan untuk membunuh kredibilitas sebelum membunuh fisik. Dalam istilah militer, ini adalah information warfare, tapi dengan bumbu licik: membungkam yang melihat, mendengar, dan mencatat. Dan jika kita tarik ke konteks lokal Indonesia, logikanya sama saja dengan ketika penguasa menuduh pengkritik sebagai “antek asing” atau “provokator” sebelum menggelar konferensi pers tentang pentingnya ketertiban.
Ada yang bilang jurnalis itu cuma saksi. Saya rasa itu salah besar. Di konflik seperti Gaza, jurnalis adalah garda depan kebenaran—dan karena itu, mereka adalah ancaman bagi siapa pun yang ingin kebenaran tetap terkubur. Ketika seorang jurnalis dibunuh, yang mati bukan hanya tubuhnya, tapi juga ribuan cerita yang tak sempat ia tulis, foto yang tak sempat ia ambil, video yang tak sempat ia rekam. Setiap pembunuhan jurnalis adalah amputasi memori kolektif.
Mungkin sebagian pembaca akan berpikir: bukankah semua ini terlalu gamblang untuk disebut kebetulan? Yah, sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa pembungkaman informasi jarang dilakukan secara spontan. Dari pembantaian jurnalis di Timor Timur hingga pembunuhan Jamal Khashoggi, selalu ada skenario yang dirancang, narasi pembenaran yang disiapkan, dan penonton yang sudah diposisikan. Bedanya, di Gaza, penontonnya adalah seluruh dunia, dan sebagian memilih memalingkan wajah.
Ironi paling getirnya? Dunia internasional punya aturan yang jelas tentang perlindungan jurnalis di medan perang—Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977—tapi aturan itu seolah hanya berlaku kalau pelanggarnya bukan sekutu strategis negara-negara besar. Pelanggaran ini tidak hanya dibiarkan, tapi juga diabaikan dalam diskursus publik internasional. Seakan-akan nyawa jurnalis Palestina punya nilai kurs yang lebih rendah di pasar politik global.
Saya kira yang paling memprihatinkan bukan hanya kematian mereka, tapi juga kematian rasa peduli publik. Di era ketika setiap orang bisa jadi “citizen journalist” lewat ponselnya, paradoksnya adalah: kita punya lebih banyak gambar tapi lebih sedikit empati. Kematian jurnalis di Gaza mungkin hanya lewat sekejap di layar Anda, diapit antara video kucing lucu dan cuplikan pertandingan sepak bola. Dan di situlah senjata paling ampuh dari pembungkaman bekerja: membuat pembunuhan jadi sekadar konten yang lewat.
Namun, ada satu hal yang sulit dibungkam: fakta bahwa bahkan setelah 237 nama itu tercatat, akan selalu ada jurnalis Palestina lain yang mengangkat kameranya. Mungkin karena mereka tahu, jika mereka diam, Gaza akan mati dua kali—pertama secara fisik, kedua secara naratif. Dan bagi mereka, kematian fisik mungkin lebih mudah ditanggung daripada kematian narasi.
Kalau pembaca merasa ini semua terlalu kelam, itu wajar. Karena kelam adalah warna asli dari kebenaran yang disembunyikan. Dan seperti kata pepatah Jawa, “Wong urip iku kudu wani”—hidup itu harus berani. Di Gaza, keberanian itu bukan soal mengangkat senjata, tapi mengangkat pena dan kamera, meski tahu ada peluru yang menunggu di ujungnya. Dan setiap kali satu kamera jatuh, dunia seharusnya merasakan kehilangan, bukan sekadar lewat tanpa bekas di linimasa.









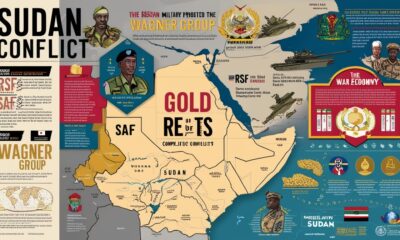

Pingback: Suara Terakhir Anas Sharif: Keberanian di Tengah Derita Gaza - vichara.id