Opini
Media Sosial: Sarang Predator, Ancaman Anak di Era Digital

Di sebuah rumah sederhana di Jepara, Jawa Tengah, seorang pemuda berusia 21 tahun bernama S menatap layar ponsel, jari-jarinya menari di atas keyboard virtual. Di balik anonimitas media sosial, ia merangkai pesan manis yang menjerat 31 anak perempuan berusia 12 hingga 17 tahun. Polda Jawa Tengah mengungkap kejahatan seksual berbasis online ini, menemukan dokumen video di ponsel S sebagai bukti. Kisah ini adalah cermin kelam bahaya media sosial bagi anak-anak, menuntut tindakan segera.
Media sosial telah menjadi ladang subur bagi predator seperti S. Teori Kriminologi Digital menjelaskan bagaimana teknologi membuka peluang kejahatan baru. S memanfaatkan Telegram untuk mendekati korban secara anonim, menggunakan foto palsu untuk merayu anak-anak yang asyik menjelajahi dunia maya. Ia lalu beralih ke WhatsApp, meminta konten sensitif dan mengancam menyebarkannya jika korban menolak. Teknologi memperluas jangkauannya, menjerat anak-anak dari Jepara hingga Lampung, menunjukkan betapa mudahnya eksploitasi di era digital.
Data memperkuat urgensi isu ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 1.247 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2023, dengan 30% melibatkan eksploitasi daring. Kasus Jepara bukanlah pengecualian, melainkan bagian dari tren nasional yang mengkhawatirkan. Teori Kriminologi Digital menyoroti bahwa fitur seperti enkripsi dan anonimitas memungkinkan predator beroperasi tanpa hambatan. Tanpa regulasi ketat, platform digital menjadi sarang kejahatan, meninggalkan anak-anak dalam bahaya konstan.
Mengapa S menjadi predator? Social Learning Theory menawarkan jawaban. Sebagai pemuda yang “mahir menggunakan media sosial,” S kemungkinan mempelajari teknik grooming dari paparan konten daring, seperti forum atau situs pornografi. Setiap keberhasilan—mendapatkan foto telanjang atau memaksa korban bertemu—memberikan penguatan positif, mendorongnya untuk terus berburu. Laporan menyebutkan bahwa lima korban disetubuhi, menunjukkan eskalasi dari manipulasi digital ke kekerasan fisik, diperkuat oleh rasa kuasa yang ia dapatkan.
Anak-anak juga terperangkap dalam dinamika pembelajaran sosial. Social Learning Theory menjelaskan mengapa korban mematuhi S meski ketakutan. Ancaman penyebaran konten, seperti disebutkan dalam laporan, menciptakan penguatan negatif: menolak berarti menghadapi rasa malu sosial. Usia 12 hingga 17 tahun adalah periode rentan, di mana anak-anak bergantung pada media sosial untuk validasi. Kombes Pol Artanto menyebutkan “beban psikologi” korban, menegaskan bahwa tekanan ini membuat mereka merasa tak berdaya.
Kerentanan anak-anak diperparah oleh rendahnya literasi digital. Teori Kriminologi Digital mengungkap bahwa anak-anak, yang “senang-senangnya menggunakan media sosial,” mudah terpikat oleh bujuk rayu. Laporan menunjukkan bahwa S memilih anak perempuan, mengeksploitasi kenaifan mereka di platform yang minim pengawasan. KPAI melaporkan bahwa hanya 15% anak Indonesia mendapat edukasi keamanan digital, sebuah celah yang dimanfaatkan predator. Tanpa pengetahuan untuk mengenali grooming, anak-anak menjadi mangsa empuk di dunia maya.
Lingkungan sosial S juga berperan. Social Learning Theory menyarankan bahwa ia mungkin terpapar norma yang menormalkan eksploitasi, seperti pornografi daring atau komunitas yang meremehkan kekerasan seksual. Meskipun laporan tidak merinci latar belakangnya, kemahirannya dalam manipulasi mengindikasikan pembelajaran dari sumber tertentu. Anonimitas digital memperkuat keyakinannya bahwa ia bisa lolos, sebuah pola yang diperparah oleh kurangnya konsekuensi awal hingga polisi menangkapnya setelah laporan keluarga korban.
Bahaya media sosial melampaui ranah daring. Laporan menyebutkan bahwa S melakukan persetubuhan di lokasi kos, menunjukkan bagaimana interaksi digital dapat berujung pada kekerasan fisik. Teori Kriminologi Digital menjelaskan bahwa teknologi menurunkan hambatan psikologis pelaku, memungkinkan perencanaan pertemuan tanpa jejak jelas. Data dari ECPAT Indonesia menunjukkan bahwa 25% kasus eksploitasi anak daring berujung pada pelecehan fisik, menggarisbawahi bahwa media sosial adalah pintu gerbang kejahatan yang lebih berat.
Negara harus bertindak tegas. Teori Kriminologi Digital menekankan perlunya regulasi platform. Pemerintah bisa memperkuat UU ITE dengan mewajibkan platform seperti Telegram dan WhatsApp menerapkan sistem deteksi dini untuk pola grooming, seperti analisis perilaku berbasis AI. Contohnya, Inggris telah menerapkan Online Safety Act yang mengharuskan platform memantau konten berbahaya. Indonesia juga perlu badan siber khusus untuk anak, mempercepat penanganan kasus seperti ini.
Pencegahan juga membutuhkan pendekatan psikologi sosial. Social Learning Theory menyarankan memutus rantai pembelajaran pelaku dengan membatasi akses ke konten berbahaya, seperti situs pornografi atau forum predator. Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa memperketat filter internet, sementara edukasi anak harus mengajarkan ketahanan terhadap ancaman. Program seperti “Internet Sehat” harus diperluas ke sekolah, mengajarkan anak untuk melapor, bukan mematuhi, mengubah pola kepatuhan menjadi keberanian.
Literasi digital adalah kunci. Teori Kriminologi Digital menunjukkan bahwa anak-anak membutuhkan pengetahuan untuk mengenali grooming, seperti permintaan konten sensitif. Laporan menyebutkan bahwa kasus terungkap berkat keluarga korban, menegaskan peran orang tua. Sekolah harus mengintegrasikan pelajaran keamanan digital, sementara orang tua memantau aktivitas anak. Data KPAI menunjukkan bahwa 70% orang tua tidak memahami risiko daring, sebuah celah yang harus ditutup melalui kampanye nasional.
Hukuman 12 tahun penjara bagi S adalah langkah awal, tetapi tidak cukup. Teori Kriminologi Digital mengingatkan bahwa konten digital bersifat permanen, memperpanjang trauma korban. Laporan menyebutkan tekanan psikologis korban, menunjukkan kebutuhan akan konseling jangka panjang. Pemerintah bisa mendirikan pusat krisis anak di setiap provinsi, menyediakan dukungan psikologis dan hukum. Masyarakat juga harus menciptakan lingkungan yang tidak menyalahkan korban, tetapi mendukung pemulihan mereka.
Kasus ini adalah alarm keras. Media sosial, dengan segala potensinya, telah menjadi sarang predator, dan anak-anak adalah korban paling rentan. Teori Kriminologi Digital dan Social Learning Theory mengungkap bagaimana teknologi dan pembelajaran sosial menciptakan lingkaran eksploitasi. Data KPAI dan ECPAT menegaskan bahwa ini bukan masalah lokal, tetapi krisis nasional. Dengan regulasi ketat, edukasi, dan dukungan korban, kita bisa menjadikan media sosial ruang yang aman.
Negara, platform, dan masyarakat harus bersatu. UU yang mewajibkan deteksi dini, filter konten berbahaya, dan edukasi masif adalah langkah mendesak. Anak-anak berhak tumbuh tanpa bayang-bayang predator di layar ponsel mereka. Kasus Jepara bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan untuk melindungi generasi masa depan dari cengkeraman kejahatan digital.









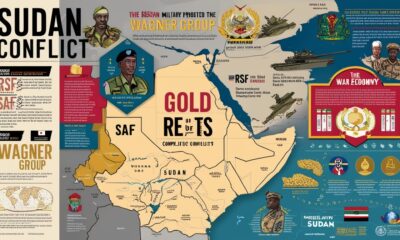

Pingback: Retaknya Kepercayaan pada Media di Era Polarisasi - vichara.id