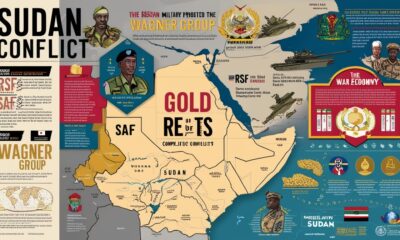Opini
Euro di Ujung Tanduk: Krisis Berikutnya Bisa Mematikan

Satu mata uang untuk menyatukan benua—betapa mulianya cita-cita itu. Ketika euro diperkenalkan, ia datang bukan hanya sebagai alat tukar, tapi sebagai simbol integrasi, janji solidaritas, dan mantra pertumbuhan. Mata uang tanpa tentara, tanpa bendera, tapi konon bisa mengalahkan keraguan sejarah dan trauma geopolitik Eropa. Namun seperti banyak utopia yang terlalu cepat dicetak dan disepakati, euro lahir dengan semacam keluguan: ia dibesarkan dalam optimisme, tetapi tak dilindungi oleh realisme.
Para pendirinya tak bisa dibilang bodoh. Mereka tahu betul risiko yang mengintai jika moneter tak disertai fiskal. Bahwa tanpa pengawasan anggaran bersama, tiap negara akan tergoda berutang lebih banyak dari yang bisa mereka bayar, lalu—seperti kebiasaan lama di masa kenakalan negara-negara berkembang—memanggil bank sentral untuk mencetak jalan keluar. Maka dibuatlah pagar: Bank Sentral Eropa hanya akan menjaga stabilitas harga, bukan jadi tukang selamatkan negara manja. Tidak ada bailout, tidak ada pelunasan utang oleh tetangga sebelah.
Tapi pagar itu ternyata punya celah. Dan krisis datang bukan dengan sopan santun. Dalam sejarahnya yang belum genap tiga dekade, euro telah dihantam serangkaian guncangan: krisis keuangan global, krisis utang Yunani, Brexit, pandemi, dan lonjakan inflasi. Setiap krisis menjadi ujian bukan hanya bagi kekuatan institusi, tetapi juga bagi narasi persatuan yang dibanggakan Eropa. Dan seperti kisah rumah tangga yang terlalu banyak kompromi tapi malas evaluasi, krisis hanya dijadikan alasan untuk menambal, bukan membongkar fondasi yang rapuh.
Cochrane menyebut ini dengan kejujuran brutal: euro dirancang secara cemerlang, tapi dibiarkan tumbuh dalam ketidaksempurnaan yang disengaja. Seperti menikah tanpa membicarakan kemungkinan perceraian—karena siapa sudi merusak momen bahagia dengan skenario pahit. Maka tak ada mekanisme default, tak ada rambu krisis, dan utang negara dibiarkan diperlakukan seolah-olah bebas risiko, padahal utang tetaplah utang. Ketika Yunani tersandung, seluruh sistem ikut limbung. Dan ketika Italia batuk, bank-bank di Jerman dan Prancis mulai demam.
Lebih lucu lagi, ketika bank-bank mulai menumpuk obligasi negara sebagai “aset aman”, mereka sejatinya sedang duduk di atas tambang waktu. Karena kalau obligasi itu gagal bayar, maka bomnya bukan hanya meledak di kas negara, tapi di sistem perbankan. Tapi toh, itu tidak menghentikan pesta. Karena selama ECB tetap bisa membeli surat utang dan menyulapnya jadi likuiditas, semua orang bisa pura-pura lupa bahwa utang sebenarnya adalah janji yang tak bisa ditunda selamanya.
Yang ironis adalah: ECB yang dulu dilarang ikut campur urusan fiskal, kini jadi penolong utama setiap krisis. Dulu disebut independen, kini jadi pengasuh yang tak punya pilihan selain turun tangan. “Whatever it takes,” kata Mario Draghi, dan seluruh pasar bertepuk tangan. Tapi yang jarang dibicarakan: ketika bank sentral terlalu sering turun tangan, ia bukan lagi wasit, melainkan pemain—dan kadang malah jadi sponsor utama pertandingan yang busuk.
Kini, situasinya jauh lebih serius. Utang publik di zona euro melonjak drastis. Italia di atas 140% PDB. Prancis mendekati 110%. Inflasi merayap naik, sementara suku bunga sempat dibiarkan rendah terlalu lama. ECB terjebak di dua kutub: menekan inflasi atau menyelamatkan obligasi negara. Jika menaikkan bunga terlalu cepat, pasar utang ambruk. Jika menahannya, inflasi menjilat fondasi kepercayaan publik. Tak ada pilihan yang benar, hanya kompromi yang makin menyakitkan.
Lalu publik bertanya: bagaimana bisa Eropa yang begitu disiplin, begitu maju, begitu terorganisasi… bisa berakhir seperti ini? Jawabannya sederhana—karena di balik jargon teknokratis dan angka-angka neraca, yang ada tetaplah negara-negara dengan kepentingan politik, pemilu lima tahunan, tekanan populis, dan elite yang lebih takut kehilangan kursi ketimbang kehilangan kredibilitas fiskal. Persis seperti negara-negara yang dulu mereka bimbing agar hemat dan rasional.
Masalahnya bukan pada krisis—krisis memang akan datang dan pergi. Masalahnya adalah ketidakmauan untuk belajar dari krisis. Setiap gempa dilewati dengan janji akan reformasi, tapi setelah debu reda, semangat itu menguap, digantikan oleh sikap “ECB pasti turun tangan lagi.” Akibatnya, moral hazard jadi budaya. Negara tak perlu reformasi, karena tahu akan diselamatkan. Investor tak perlu waspada, karena tahu akan diganjar likuiditas. Bank tak perlu hati-hati, karena tahu negara tak akan dibiarkan jatuh.
Kita bisa membayangkan skenario paling buruk. Satu negara besar gagal bayar. Bank-bank goyah. Pasar panik. Dana-dana pensiun terpukul. Pemerintah harus memangkas belanja. Warga turun ke jalan. Ketimpangan melebar. Oposisi kanan dan kiri ekstrem naik daun. Diskusi tentang keluarnya suatu negara dari euro bukan lagi bahan humor, tapi agenda parlemen. Euro bisa bertahan dari satu krisis, dua krisis, tapi apakah ia bisa bertahan dari badai simultan di tiga front: utang, bank, dan politik?
Dan jangan lupa, ini bukan cuma urusan Brussels atau Frankfurt. Efeknya bisa terasa sampai ke sini. Dalam dunia yang begitu terhubung, gejolak pasar Eropa akan menjalar ke pasar global, termasuk Asia Tenggara. Rupiah bisa ikut tertekan, ekspor bisa terganggu, dan investor akan lebih pilih menaruh uangnya di tempat yang dianggap “aman”—meski kadang tempat itu hanya tampak aman karena sedang belum disorot.
Lucunya, banyak pemimpin Eropa masih berbicara seolah waktu ada di pihak mereka. Padahal waktu bukan sekutu, tapi pengingat yang kejam. Setiap tahun yang dihabiskan tanpa reformasi adalah satu batu lagi di punggung euro, menunggu saat tepat untuk runtuh.
Apakah Eropa akan hancur? Tidak juga. Tapi apakah bisa lebih buruk dari sebelumnya? Sangat mungkin. Dan ketika hari itu tiba, tak akan ada pidato “whatever it takes” yang bisa menyembunyikan fakta bahwa ini bukan krisis yang tiba-tiba datang. Ini krisis yang dibangun dengan penuh kesadaran, dari keputusan-keputusan yang terlalu nyaman untuk ditolak, dan terlalu berbahaya untuk diulang. Tapi toh diulang juga.
Karena dalam banyak hal, krisis Eropa bukan tentang kekurangan teknis, melainkan kelebihan optimisme—dan keberanian yang selalu datang terlambat.