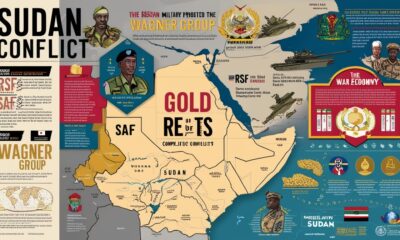Opini
Eropa Di Ambang Krisis Air, Kok Bisa?

Di tengah kekhawatiran yang makin nyata, Komisi Eropa mulai mengambil langkah serius. Mereka tengah merancang seruan kepada negara-negara anggota Uni Eropa untuk memangkas penggunaan air setidaknya 10 persen sebelum 2030. Draf rencana yang bocor ke Financial Times ini bukan sekadar kebijakan teknis. Ia adalah isyarat—jeritan sunyi dari benua yang makin terdesak oleh krisis air yang tak pernah mereka bayangkan datang secepat ini.
Air, sumber kehidupan yang dulu begitu melimpah di Eropa, kini menyusut diam-diam. Kekeringan yang berulang, kebakaran hutan, hingga banjir besar yang menghancurkan infrastruktur telah merugikan benua ini hingga miliaran euro. Dan jika Eropa, dengan segala keunggulan teknologi dan sistemnya, mulai goyah, maka kita pun patut bertanya: bagaimana nasib kawasan seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia?
Air Tanah Eropa Menyusut, Infrastruktur Bocor
Kondisi di lapangan tak bisa dipungkiri lagi. Cadangan air tanah di sejumlah wilayah Eropa telah turun ke level terendah dalam sejarah pencatatan. Di Yunani, misalnya, perusahaan air EYDAP memperingatkan bahwa Athena bisa kehabisan air dalam dua tahun jika musim kering terus berlanjut. Di Siprus, Menteri Pertanian Maria Panayiotou menyebut 2025 bisa menjadi tahun ketiga kekeringan beruntun—salah satu periode paling parah dalam setengah abad terakhir.
Larangan mengisi ulang kolam renang mulai diberlakukan di selatan Eropa. Di Swedia, beberapa wilayah melarang penyiraman taman dengan selang air. Di Prancis dan Spanyol, konflik antara petani dan aktivis lingkungan soal akses air mencerminkan tekanan yang semakin besar. Bahkan pada 2023, para petani di Jerman dan Polandia berdemonstrasi menolak kebijakan lingkungan Uni Eropa yang dianggap membatasi akses mereka terhadap air dan bahan pertanian.
Krisis ini diperparah oleh infrastruktur yang ketinggalan zaman. EurEau, organisasi industri air Eropa, mencatat bahwa sekitar 25 persen air bersih hilang karena pipa-pipa yang bocor. Di Bulgaria, kebocoran ini bahkan mencapai 60 persen. Komisi Eropa memperkirakan dibutuhkan €23 miliar per tahun untuk memperbaiki sistem ini, sementara Bank Investasi Eropa baru menjanjikan sekitar €15 miliar untuk periode 2025–2027.
Daur Ulang Minim, Padahal Potensial
Yang juga mencengangkan, hanya 2,4 persen air di Uni Eropa saat ini yang didaur ulang. Padahal teknologi dan praktik daur ulang air sudah tersedia, tinggal kemauan politik dan kesadaran publik yang perlu didorong. Komisioner Lingkungan UE, Jessika Roswall, mengingatkan bahwa Eropa harus segera mengubah cara pandang terhadap air. “Kita perlu berpikir ulang tentang bagaimana menggunakan air secara lebih efisien,” ujarnya. Pesan ini bukan hanya untuk mereka yang mengelola sistem, tapi juga untuk warga biasa: dari kamar mandi hingga dapur.
Ini bukan semata-mata soal lingkungan. Ini juga soal ekonomi dan stabilitas sosial. Bank Sentral Eropa memperkirakan bahwa kelangkaan air permukaan dapat mengurangi Produk Domestik Bruto (PDB) zona euro hingga 15 persen. Risiko konflik lintas batas akibat perebutan air juga mulai diperhitungkan dalam kebijakan luar negeri Eropa.
Kita di Indonesia, Apakah Siap?
Kondisi Indonesia memang berbeda. Kita dikaruniai curah hujan tinggi, memiliki ribuan sungai besar seperti Kapuas dan Mahakam, serta danau luas seperti Toba. Tapi kekayaan ini menyimpan paradoks. Di Pulau Jawa—yang menampung 60 persen penduduk Indonesia—kekeringan musiman kian sering melanda, terutama di daerah Jawa Timur, DIY, dan Nusa Tenggara. Sementara itu, Jakarta yang langganan banjir justru masih kesulitan menyediakan air bersih untuk seluruh warganya. Menurut BPS, pada 2023 sekitar 20 persen rumah tangga Indonesia belum memiliki akses terhadap air minum layak.
Kita pun tak luput dari infrastruktur yang rentan. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di banyak kota kehilangan 30 hingga 50 persen air bersih karena kebocoran. Sama seperti di Eropa, air yang seharusnya sampai ke rumah warga justru mengalir sia-sia ke tanah. Padahal, anggaran perbaikan jauh lebih terbatas dari yang dimiliki Eropa.
Krisis Air: Buatan Manusia dan Alam Sekaligus
Persoalan kita bukan hanya soal distribusi. Pencemaran memperparah masalah. Sungai Citarum, yang menjadi ikon buruk pencemaran air, tercemar berat oleh limbah industri, domestik, dan pertanian. Deforestasi di Kalimantan dan Sumatera mengurangi daya serap tanah terhadap hujan, memperbesar risiko banjir dan longsor. Urbanisasi cepat di kota-kota besar menyebabkan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan—termasuk di Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
Perubahan iklim memperumit semuanya. Pola hujan berubah drastis. Musim kemarau makin panjang, musim hujan datang tiba-tiba dan ekstrem. Kenaikan muka laut mengancam air tanah pesisir dengan intrusi air asin. Pertanian, yang menyerap hampir 70 persen air bersih kita, makin rentan terganggu. Kekeringan berarti gagal panen. Gagal panen berarti naiknya harga pangan, yang ujungnya memperdalam kemiskinan.
Belajar dari Eropa: Dari Krisis Menuju Aksi
Apa yang bisa kita pelajari dari Eropa?
Pertama, perlunya target nasional untuk penghematan air. Seperti target 10 persen Eropa, Indonesia juga bisa menetapkan target serupa yang realistis namun mendorong kesadaran luas—baik di sektor rumah tangga, industri, maupun pertanian.
Kedua, memperkuat teknologi daur ulang air. Teknologi ini bukan hal baru, tapi implementasinya masih minim. Beberapa kota seperti Surabaya sudah mulai menerapkan sistem pengolahan air limbah domestik menjadi air bersih, tapi belum menyebar secara nasional.
Ketiga, investasi dan pembenahan sistem distribusi air harus menjadi prioritas. Tak cukup hanya membangun waduk atau embung. Kita perlu memastikan air yang diolah bisa sampai ke warga dengan efisien.
Keempat, penegakan hukum atas pencemaran harus diperkuat. Sudah saatnya ada sinergi nyata antara KLHK, Pemda, dan penegak hukum untuk menghentikan pencemaran air, terutama oleh industri besar.
Dan terakhir, edukasi publik yang konsisten dan berkelanjutan. Krisis air adalah krisis budaya. Kita terbiasa menganggap air sebagai sumber daya tak terbatas, padahal ia bisa habis. Kesadaran harus dibentuk sejak bangku sekolah, melalui kurikulum, media, dan keteladanan.
Kapan Kita Mulai?
Tulisan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Jika Eropa—yang punya dana, teknologi, dan sistem tata kelola yang baik—saja bisa kalang kabut menghadapi krisis air, maka Indonesia harus lebih sigap dari sekarang. Sebab air bukan milik abadi. Ia bisa hilang, berubah arah, atau mencelakai jika kita lengah.
Eropa sedang berlari menyelamatkan air mereka. Kita, dengan segala potensi dan tantangan, harus mulai melangkah. Sebelum terlambat.