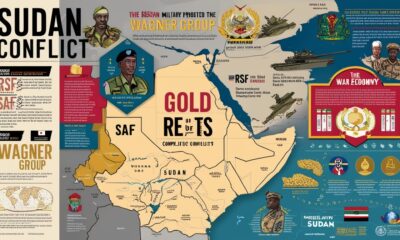Opini
100 Ribu Ton Bom untuk Gaza: Dunia Masih Diam?

Deru mesin pesawat itu bukan sekadar denting logam yang menembus langit Timur Tengah. Ia membawa muatan senjata, menambah tumpukan kematian yang mengubur Gaza dalam reruntuhan. Bukan lagi hitungan satu atau dua kiriman, melainkan ratusan penerbangan kargo dari Amerika Serikat yang telah menuangkan lebih dari 90.000 ton persenjataan ke Israel sejak perang meletus pada Oktober 2023. Di balik angka yang dingin itu, ada panas ledakan yang menghanguskan rumah, sekolah, bahkan tubuh-tubuh mungil yang tak mengerti arti perang.
Pemerintah Israel menyebut kiriman itu sebagai “komponen signifikan” bagi operasi militer yang kini memasuki bulan ke-20. Di Gaza, realitasnya adalah 54.000 nyawa melayang—dan lebih dari separuhnya adalah perempuan, anak-anak, dan lansia, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. The Lancet memperkirakan jumlah kematian sebenarnya bisa 41 persen lebih tinggi. Angka itu tak mampu menyampaikan seluruh kepedihan—tapi kesaksian dokter Victoria Rose di Rumah Sakit Nasser, Khan Yunis, berbicara lebih keras. Dengan suara gemetar, ia menggambarkan luka-luka mengerikan yang dialami anak-anak akibat ledakan. “Saya belum pernah melihat cedera sebesar ini,” katanya.
Sementara itu, di seberang samudra, di warung kopi Jakarta dan masjid-masjid Yogyakarta, berita dari Gaza terus menggema. Solidaritas tumbuh, tak hanya dalam bentuk doa dan poster “Free Palestine,” tapi juga aksi nyata: penggalangan dana, demonstrasi besar, pengiriman relawan kemanusiaan. Namun laporan investigatif dari The Cradle mengusik nurani kita lebih dalam—bahwa Amerika Serikat, dalam 19 bulan terakhir, telah menyetujui penjualan senjata senilai lebih dari 30 miliar dolar. Termasuk di antaranya adalah 7,4 miliar dolar untuk rudal dan bom pada Februari 2025, serta paket “darurat” senilai 3 miliar dolar pada bulan berikutnya.
Lebih dari 100.000 ton bahan peledak telah menghantam Gaza—tiga kali lipat lebih banyak daripada bom yang dijatuhkan Jerman ke London saat Blitz di Perang Dunia II. Ini bukan lagi sekadar dukungan logistik atau aliansi militer. Ini adalah bahan bakar kehancuran massal. Dan di tengah lautan puing itu, seorang dokter asing menyaksikan anak-anak yang tubuhnya sobek oleh serpihan logam, sementara para relawan dari MER-C Indonesia ikut berjuang menyelamatkan mereka. Tak ada statistik yang bisa menggambarkan jeritan ibu yang kehilangan anaknya dalam satu ledakan.
Angka-angka ini—54.000 kematian, 2.180 keluarga lenyap seutuhnya—memaksa kita berhenti dan bertanya: ini masihkah disebut konflik, atau sudah menjelma jadi tragedi kemanusiaan yang mengguncang nurani global? Dan kita di Indonesia, dengan sejarah panjang solidaritas terhadap Palestina, tak bisa hanya berdiri sebagai penonton.
AS berdiri sebagai penopang utama kekuatan militer Israel. Laporan Costs of War dari Brown University mencatat bahwa antara Oktober 2023 hingga September 2024, Washington menghabiskan 22,76 miliar dolar untuk mendukung operasi Israel. Dengan menggunakan otoritas darurat, Departemen Luar Negeri AS mempercepat pengiriman senjata tanpa pengawasan kongres yang ketat. Bahkan ketika ada upaya legislatif untuk menghentikan transfer itu, Senat menolaknya—bukan dengan suara terbagi, tapi dengan keputusan bulat.
Di tengah semangat Amerika yang mengkampanyekan demokrasi dan hak asasi manusia, muncul pertanyaan: bagaimana bisa negara yang mengklaim sebagai penjaga perdamaian begitu leluasa mengalirkan senjata ke zona konflik? Apakah ini semata soal geopolitik dan aliansi strategis, atau justru bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab kemanusiaan?
Sementara itu, reaksi dunia internasional masih terpecah. Negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania menyerukan gencatan senjata, namun perjanjian damai mereka dengan Israel membatasi langkah-langkah tegas. Arab Saudi, berdasarkan laporan Al Jazeera, tampak lebih tertarik merundingkan normalisasi hubungan dengan Israel demi agenda ekonomi dan stabilitas regional. Qatar dan Turki mencoba menjadi juru damai, tapi mediasi mereka kerap berakhir buntu. Di Eropa, suara pun tak seragam—Prancis dan Spanyol menyerukan embargo senjata, sedangkan Jerman tetap menjadi pemasok utama setelah AS.
PBB melalui UNRWA menyatakan bahwa Gaza menghadapi “kelaparan buatan manusia.” Blokade dan serangan membuat distribusi makanan dan obat-obatan nyaris mustahil. Namun, upaya untuk menghentikan kekerasan terus tersandung veto AS di Dewan Keamanan.
Solidaritas Indonesia terhadap Palestina sudah lama tumbuh. Kita menyaksikan demonstrasi besar di Monas, penggalangan dana di Surabaya, hingga doa berjamaah di masjid-masjid Aceh. Tapi apakah itu cukup? Laporan ini menantang kita untuk melangkah lebih jauh. Sebagai negara non-blok dengan posisi strategis di Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia memiliki peluang untuk mengusulkan investigasi independen melalui PBB atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC), seperti yang diserukan Human Rights Watch. Kita juga bisa menekan negara-negara besar di forum G20 untuk mendesak gencatan senjata, atau memperkuat dukungan bagi lembaga kemanusiaan seperti MER-C melalui jalur resmi.
Pernyataan Netanyahu yang menyebut Donald Trump sebagai “teman terbesar Israel” menambah dimensi lain dalam konflik ini. Meski hubungan keduanya dikabarkan retak akibat perbedaan kepentingan regional, seperti normalisasi dengan Teluk, aliansi strategis AS-Israel tetap kokoh. Pesawat kargo terus mendarat. Kapal logistik terus berlabuh. Bahkan janji-janji tentang “Riviera Timur Tengah” pascakonflik terasa sinis ketika bom masih berjatuhan.
The Cradle menggunakan istilah “genosida”—sebuah kata berat yang sarat muatan hukum. Konvensi Genosida 1948 mensyaratkan adanya niat untuk menghancurkan kelompok tertentu. Amnesty International dan Human Rights Watch telah mencatat pola serangan tidak proporsional, tapi keputusan akhir tetap berada di tangan ICC, yang saat ini tengah menyelidiki. Namun satu hal tak terbantahkan: 100.000 ton bahan peledak telah menghapus ribuan keluarga dari peta, menyisakan pertanyaan tentang batas antara dukungan dan keterlibatan dalam penderitaan.
Indonesia, dengan pengalamannya menghadapi konflik—dari Aceh hingga Papua—mengerti luka akibat kekerasan bersenjata. Gaza, dengan skala kehancuran yang jauh lebih masif, menjadi cermin sekaligus seruan. Bukan hanya untuk menyumbang atau berunjuk rasa, tapi untuk mengambil langkah nyata di forum internasional. Menyerukan embargo, mendorong penyelidikan, atau sekadar menjaga agar Gaza tak hilang dari percakapan dunia.
Saat malam tiba dan lampu-lampu kota menyala di Jakarta, kita mungkin merasa jauh dari Gaza. Tapi suara dokter di Khan Yunis yang berkata, “Saya belum pernah melihat luka seperti ini,” seharusnya menggema ke relung hati kita. Gaza tak butuh belas kasihan. Ia butuh keberpihakan. Dunia sedang menyaksikan. Kita akan diam, atau bertindak?