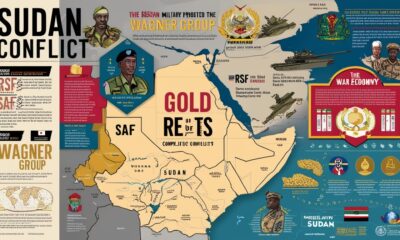Analisis
Jejak Panjang Kudeta Amerika di Venezuela

Ada ironi yang sulit ditelan ketika sebuah negara yang mengaku sebagai mercusuar demokrasi dunia justru begitu gigih menumbangkan pemerintahan sah negara lain. Amerika Serikat, dengan segala benderang jargon kebebasan dan hak asasi, berkali-kali menunjukkan wajah aslinya di Venezuela. Hari ini, melalui laporan Politico, kita kembali disuguhi rencana baru yang menggeser fokus militer dari Tiongkok ke Amerika Latin. Sekilas terdengar teknis, tetapi jika ditelusuri lebih jauh, ini bukan sekadar strategi militer. Ini adalah babak baru dari obsesi lama: bagaimana menjinakkan Caracas.
Kita masih ingat bagaimana Washington beberapa tahun lalu mendadak “mencetak” seorang presiden tandingan bernama Juan Guaidó. Seorang tokoh oposisi yang mungkin lebih dikenal di ruang redaksi media Barat ketimbang di pasar-pasar rakyat Venezuela. Dengan percaya diri, Amerika Serikat dan sekutunya mengakui Guaidó sebagai pemimpin sah, seolah kehendak rakyat bisa ditentukan lewat pengakuan diplomatik. Namun realitas berbicara lain: tanpa dukungan militer dan birokrasi, Guaidó hanyalah bayangan, dan bayangan tak bisa memerintah sebuah negara. Kudeta gaya elegan ini pun runtuh, meninggalkan jejak cemooh di dalam negeri Venezuela sendiri.
Tak berhenti di sana, AS menekan Venezuela dengan sanksi ekonomi yang brutal. Minyak, yang menjadi nadi perekonomian negeri itu, dibekap sampai hampir mati. Bank-bank internasional diperintahkan menjauh, transaksi finansial diblokir, kapal-kapal minyak diburu. Tujuannya sederhana: membuat rakyat lapar, marah, lalu menggulingkan Nicolás Maduro. Tapi apa yang terjadi? Di tengah kepungan sanksi, muncul solidaritas baru. Iran mengirim tanker-tanker bahan bakar yang dikawal ketat, menembus ancaman penyitaan di laut. Sebuah momen yang tak hanya menyelamatkan energi Venezuela, tapi juga memperlihatkan retaknya taring Amerika. Dunia menyaksikan, hegemoni yang dulu tak terbantahkan kini bisa ditantang oleh negara-negara yang sama-sama terhimpit.
Namun jika kita tarik mundur ke belakang, jelas bahwa obsesi Washington terhadap Caracas bukanlah cerita baru. Tahun 2002, kudeta militer sempat menjatuhkan Hugo Chávez—pendahulu Maduro—selama dua hari. Presiden yang berani menasionalisasi minyak itu diculik, pemerintahan sementara dibentuk, dan media Barat beramai-ramai menyambutnya sebagai kemenangan demokrasi. Tapi rakyat turun ke jalan, militer loyalis bergerak, dan Chávez kembali ke kursinya. Kudeta yang diyakini tak lepas dari tangan CIA itu gagal, tetapi meninggalkan luka mendalam dan memperlihatkan pola intervensi yang terus diulang.
Lalu pada 2020, kita disuguhi tontonan lain: Operasi Gideon. Sebuah operasi mercenary konyol yang dilancarkan oleh kelompok kecil mantan tentara AS dan oposisi Venezuela. Mereka berusaha menyusup lewat laut, berharap bisa memicu pemberontakan dan menangkap Maduro. Hasilnya tragis sekaligus memalukan: ditangkap bahkan sebelum sempat menembakkan peluru. Foto-foto tentara bayaran itu diikat dan diinterogasi beredar luas, menjadi simbol betapa ambisi kudeta bisa jatuh ke tingkat parodi. Namun di balik kelucuannya, ada ironi serius: mengapa sebuah negara adidaya terus-menerus merendahkan diri dengan skenario kudeta yang berkali-kali gagal?
Selain kudeta fisik, ada pula kudeta narasi. Perang informasi dan diplomasi dijalankan dengan intens. Media Barat nyaris seragam melabeli Maduro sebagai diktator, menyorot kelangkaan pangan dan antrian panjang, sembari menutup rapat fakta bahwa sanksi AS-lah yang memperparah keadaan. Seolah-olah kesengsaraan rakyat Venezuela lahir murni dari ketidakmampuan pemerintah, bukan dari blokade ekonomi yang menghancurkan. Dunia internasional pun dipaksa memilih: ikut mengecam Caracas, atau berisiko dihukum oleh Washington. Inilah perang diam-diam yang tak kalah brutal, karena senjatanya adalah opini global yang dibentuk secara sistematis.
Saya rasa, di titik ini kita bisa melihat pola yang berulang: Washington selalu menjustifikasi intervensi dengan narasi moral—menyelamatkan demokrasi, melawan diktator, atau menahan arus narkoba. Namun ketika dilihat dari dekat, alasan-alasan itu tak lebih dari topeng. Laporan terbaru bahkan menunjukkan bahwa Trump menandatangani perintah eksekutif mengubah nama Department of Defense menjadi “War Department.” Nama yang lebih jujur, memang, karena bukankah yang mereka lakukan di Amerika Latin hanyalah menabur perang, menciptakan krisis, lalu menjual diri sebagai penyelamat?
Mari kita bayangkan sejenak. Ribuan pasukan Garda Nasional ditempatkan di kota-kota besar AS, sebuah zona militer didirikan di perbatasan dengan Meksiko, kapal perang dan jet tempur dikerahkan di Karibia. Semua itu disebut demi menghentikan “banjir narkoba dari Venezuela.” Retorika yang terdengar mirip cerita sinetron politik murahan, di mana penjahat selalu datang dari luar negeri, padahal masalah utama justru bersumber dari dalam. Bukankah ironi ketika negara dengan konsumsi narkoba terbesar di dunia menunjuk jari ke tetangganya sebagai kambing hitam?
Kalau kita tarik ke konteks lokal, kisah ini seperti seorang tetangga kaya yang selalu ribut karena merasa halaman rumahnya terganggu oleh bau masakan dari dapur sebelah. Alih-alih bicara baik-baik, ia membawa preman, memutus aliran listrik, lalu menuduh tetangganya sebagai biang masalah lingkungan. Semua orang di kampung tahu siapa yang sebenarnya mengganggu, tapi siapa berani melawan? Nah, Venezuela berani melawan, dan itu yang membuat Washington kian gerah.
Kita semua tahu, Amerika Latin bukanlah wilayah asing bagi intervensi AS. Dari kudeta di Chili terhadap Salvador Allende, intervensi di Nikaragua, hingga pendudukan di Panama, sejarahnya panjang dan berdarah. Venezuela hanya episode terbaru dalam serial lama yang diputar ulang dengan aktor berbeda, tapi skenario serupa. Kali ini, tantangan semakin berat bagi Washington, karena dunia tak lagi sepenuhnya tunduk. Rusia, Tiongkok, dan Iran hadir sebagai pemberi dukungan, meski dengan motif masing-masing. Artinya, skenario yang dulu mulus kini menjadi pertaruhan besar.
Pertanyaannya, mengapa AS begitu ngotot? Jawabannya sederhana: minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Selama pemerintahan Hugo Chávez dan Maduro, minyak itu tidak sepenuhnya mengalir ke perusahaan-perusahaan Barat, tetapi digunakan untuk mendanai program sosial dalam negeri dan kerja sama dengan negara-negara non-Barat. Inilah dosa terbesar Venezuela di mata Washington: berani mengelola kekayaan sendiri tanpa tunduk pada kepentingan kapital global.
Laporan Politico yang menyebut kemungkinan penarikan pasukan dari Eropa untuk dipindahkan ke Amerika Latin jelas menunjukkan skala obsesinya. Bayangkan, komitmen kepada NATO, yang selama ini dianggap sakral, bisa dikorbankan hanya demi menghadapi Caracas. Sebuah keputusan yang bukan hanya mengguncang sekutu Eropa, tetapi juga mengonfirmasi bahwa bagi AS, demokrasi hanyalah retorika. Kepentinganlah yang sejati.
Saya tak bisa tidak melihat ini sebagai tanda keputusasaan. Amerika yang dulu merasa mampu menjaga “ketertiban dunia” kini justru memusatkan energi di halaman belakangnya sendiri, takut kehilangan kontrol. Ada semacam pengakuan diam-diam bahwa pengaruh globalnya menurun. Dunia semakin multipolar, dan setiap upaya untuk menjatuhkan Venezuela justru membuka mata banyak orang bahwa raksasa itu sedang limbung.
Kita bisa memilih untuk tersenyum getir atau marah. Tersenyum karena ironi ini begitu telanjang: negara adidaya yang mengklaim menegakkan demokrasi malah berulang kali gagal melawan negara yang ekonominya terkepung. Atau marah, karena setiap sanksi, setiap blokade, setiap ancaman perang pada akhirnya menghantam rakyat kecil—ibu-ibu yang harus mengantre minyak, anak-anak yang kekurangan gizi, pekerja yang kehilangan pekerjaan. Inilah harga dari ambisi geopolitik yang tak manusiawi.
Pada akhirnya, jejak panjang kudeta Amerika di Venezuela adalah pengingat pahit bahwa demokrasi seringkali hanya jargon kosong jika sudah berbenturan dengan minyak dan kekuasaan. Kita, yang hidup jauh di Indonesia, tetap bisa belajar darinya: betapa pentingnya menjaga kedaulatan, betapa licinnya bahasa politik internasional, dan betapa bahayanya bila kita menyerahkan kendali sumber daya kepada pihak luar. Karena kalau Venezuela bisa jadi sasaran berkali-kali, apa jaminan negara lain aman dari nasib serupa?