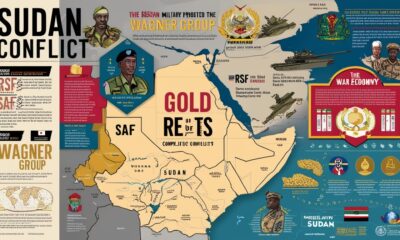Opini
Columbia Tunduk: Kampus Dijual demi Kekuasaan

Malam itu di New York, kampus Columbia tak lagi sekadar pusat intelektual. Ia menjelma menjadi panggung teater absurd: universitas bergengsi membayar lebih dari $200 juta—bukan untuk membangun laboratorium, bukan untuk riset kanker, bukan untuk beasiswa mahasiswa miskin—melainkan untuk meredakan amarah sebuah pemerintahan yang alergi terhadap protes dan sensitif pada solidaritas. Dunia akademik yang katanya merdeka, kini harus “membeli kembali” kemerdekaannya dengan membayar tebusan ke negara. Ironis, bukan?
Apa yang sedang kita saksikan ini bukan sekadar transaksi finansial. Ini pengakuan: Columbia, satu dari ikon pendidikan Amerika, ditarik turun dari singgasana otonomi, lalu diseret masuk ke arena negosiasi politis yang menjijikkan. Mereka tidak hanya dipaksa membayar denda, tapi juga mengadopsi definisi antisemitisme versi IHRA—sebuah dokumen ambigu yang seringkali dipakai untuk menyamakan kritik terhadap zionisme dengan kebencian terhadap Yahudi. Entah siapa yang menciptakan logika ini, tapi jelas ini bukan sekadar persoalan semantik. Ini alat kuasa, dan Columbia akhirnya menyanggupi untuk memakainya.
Kita tak sedang bicara soal antisemitisme sungguhan—karena siapa pun yang waras tentu menolak kebencian atas dasar identitas etnis atau agama. Tapi menggunakan antisemitisme sebagai tameng untuk membungkam solidaritas terhadap Palestina? Di sinilah letak kejinya. Ketika mahasiswa memprotes pembantaian di Gaza, menyuarakan keadilan, dan menuntut kemanusiaan, mereka dicap pembuat onar. Lalu universitas, bukannya menjadi pelindung ruang kritis, justru memanggil polisi, mendenda, dan akhirnya… tunduk pada tekanan Washington.
Lucunya, semua ini dikemas dengan label “reformasi institusional.” Revisi sistem disiplin mahasiswa, penunjukan pemantau independen dari pemerintah, hingga adopsi definisi antisemitisme sebagai syarat dikembalikannya dana riset senilai $400 juta. Kita tahu betapa pentingnya dana itu bagi universitas. Tapi ketika uang menjadi alasan untuk merobohkan prinsip, kampus bukan lagi rumah ilmu—ia telah menjadi showroom kekuasaan.
Dan bukan hanya Columbia. Pemerintahan Trump melancarkan blitzkrieg ke kampus-kampus elite: Cornell, Brown, Northwestern, Princeton. Semua diancam pembekuan dana jika tak patuh. Harvard bahkan menjadi sasaran empuk, karena berani melawan. Lebih dari $2,2 miliar dana riset dibekukan. Program mahasiswa internasional diblokir. F-1 dan J-1 disuruh pulang. Semua gara-gara Harvard tak mau menghapus program DEI, tak mau tunduk pada “audit keragaman pandangan,” dan—barangkali dosa terbesar—membiarkan mahasiswa bicara soal Palestina tanpa diborgol opini.
Ya, ini bukan sekadar tentang antisemitisme. Ini tentang siapa yang boleh bicara, dan siapa yang harus diam. Ini tentang bagaimana negara bisa mengatur opini, menentukan mana “dissent” yang sah dan mana yang dianggap “berbahaya.” Ini tentang bagaimana solidaritas bisa didelegitimasi lewat retorika keamanan, dan bagaimana kampus dipaksa menjadi perpanjangan tangan kebijakan luar negeri.
Kita yang di sini, di ujung dunia lain bernama Indonesia, mungkin merasa ini terlalu jauh. Tapi lihatlah baik-baik: bagaimana standar ganda bekerja di mana-mana. Ketika mahasiswa kita menyuarakan dukungan untuk Gaza, mereka disambut dengan curiga. Spanduk diturunkan. Forum dibubarkan. Dan selalu ada narasi bahwa ini “membahayakan toleransi.” Padahal, yang membahayakan toleransi adalah ketakutan kita sendiri terhadap perbedaan pandangan. Jika solidaritas dianggap subversif, lalu di mana tempatnya keberpihakan?
Saya teringat obrolan dengan seorang mahasiswa yang kecewa berat dengan universitasnya. “Kampus tempat gue kuliah kayaknya lebih takut sama reaksi media sosial daripada nuraninya sendiri,” katanya. Saya hanya bisa mengangguk. Karena faktanya, banyak lembaga pendidikan, di mana pun, lebih khawatir pada rating, reputasi, dan dana hibah ketimbang pembelaan atas nilai-nilai dasar seperti kebebasan akademik dan kemanusiaan. Columbia hanya contoh paling mahal dari kompromi itu.
Betapa memalukan ketika solidaritas kepada Palestina justru dianggap pelanggaran, sementara diam atas genosida dianggap kebijakan yang moderat. Dunia kita sedang menyaksikan terbaliknya etika dalam skala massal. Dan mereka yang paling dulu tahu betapa kotornya ini—para profesor, dekan, rektor—justru sibuk menyesuaikan argumen. Dari mereka, kita belajar bahwa kepengecutan bisa dibungkus dengan jargon reformasi.
Jika universitas yang digadang-gadang sebagai benteng kebebasan akademik saja bisa diremukkan dengan cek senilai $200 juta, lalu siapa lagi yang bisa melawan? Dan apakah memang semuanya harus dimulai dari pertanyaan: “Apakah ini akan membahayakan pendanaan?”
Columbia mungkin bisa menyewa “monitor independen” untuk memastikan mereka tak lagi kecolongan. Tapi siapa yang akan memonitor nurani kita? Siapa yang akan menjamin bahwa suara-suara mahasiswa yang berani tak akan lagi dikriminalisasi atas nama ketertiban? Siapa yang akan memastikan bahwa kita tidak terbiasa melihat kekejaman sambil memalingkan wajah?
Dan barangkali inilah tragedi sebenarnya: ketika universitas—tempat yang seharusnya menjadi mercusuar moral dan logika—justru mengajari kita cara paling efisien untuk menukar nilai dengan kekuasaan. Dengan manis, dengan legal, dengan sangat akademik.
Akhirnya, saya hanya bisa membayangkan: bagaimana jika universitas-universitas itu, termasuk yang di Indonesia, suatu hari juga dipaksa memilih—antara keberpihakan pada suara yang dibungkam atau pada kuasa yang membungkam? Apakah mereka akan memilih keberanian… atau kenyamanan?
Kalau melihat Columbia, kita tahu jawabannya.